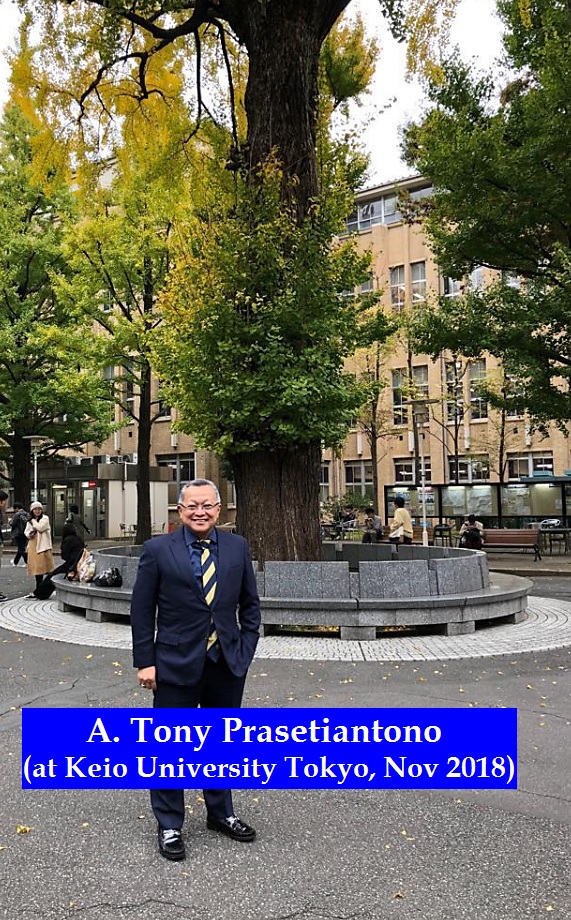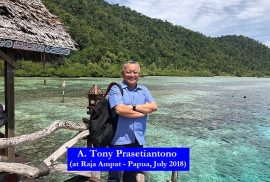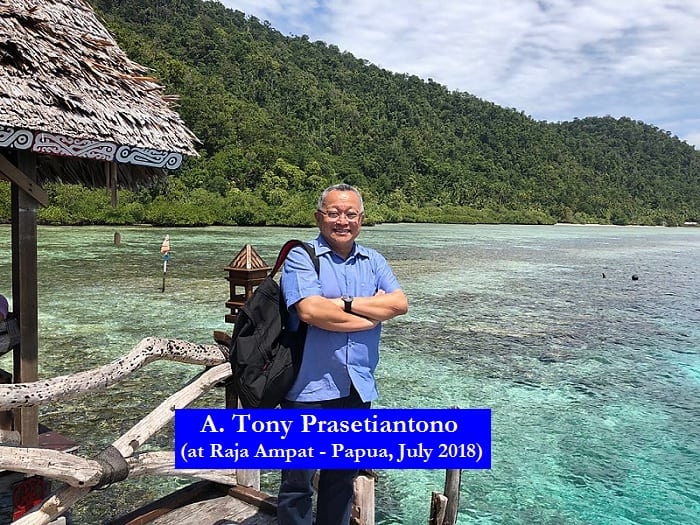Kompas – Analisis Ekonomi, Selasa 8 Januari 2019
Tidak satu pun di antara kita yang tidak menyadari, bahwa perekonomian 2019 masih akan tetap sulit. Jalan masih terjal. Ibarat lorong gelap, banyak hal yang tetap belum ketahuan ujungnya. Perekonomian global masih dicekam ketidakpastian. Perang dagang AS-China belum reda; suku bunga AS masih berpotensi naik; harga minyak dunia belum stabil. Namun, apakah semua ini akan berujung pada pesimisme perekonomian Indonesia ? Saya rasa tidak. Masih ada ruang bagi kita untuk bergerak.



 Media Indonesia, Senin 10 Desember 2018
Media Indonesia, Senin 10 Desember 2018