 Kompas – Opini, Senin 30 April 2018
Kompas – Opini, Senin 30 April 2018
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kini telah berjalan 3,5 tahun, atau mencapai 70 persen dari periode kepresidenannya, 2014-2019. Meski masih tersisa 30 persen, namun mazhab perekonomian yang dianut oleh Presiden Jokowi (Economics of Jokowi, Jokowinomics atau Ekonomika Jokowi) sudah tergambar dengan jelas. Pembangunanan infrastruktur besar-besaran menjadi paling menonjol.
Hanya saja, banyak orang yang kurang menyadari bahwa pembangunan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang, yang tidak bisa segera dipetik hasilnya. Di China, Deng Xiaoping memulai reformasi perekonomian sejak 1979, yang meliputi pembangunan infrastruktur, menarik investasi asing (termasuk dari diaspora China), dan membuka zona-zona ekonomi bebas pajak, baru merasakan “panen raya” sesudah 2000.



 Kompas – Analisis Ekonomi, Selasa 10 April 2018
Kompas – Analisis Ekonomi, Selasa 10 April 2018


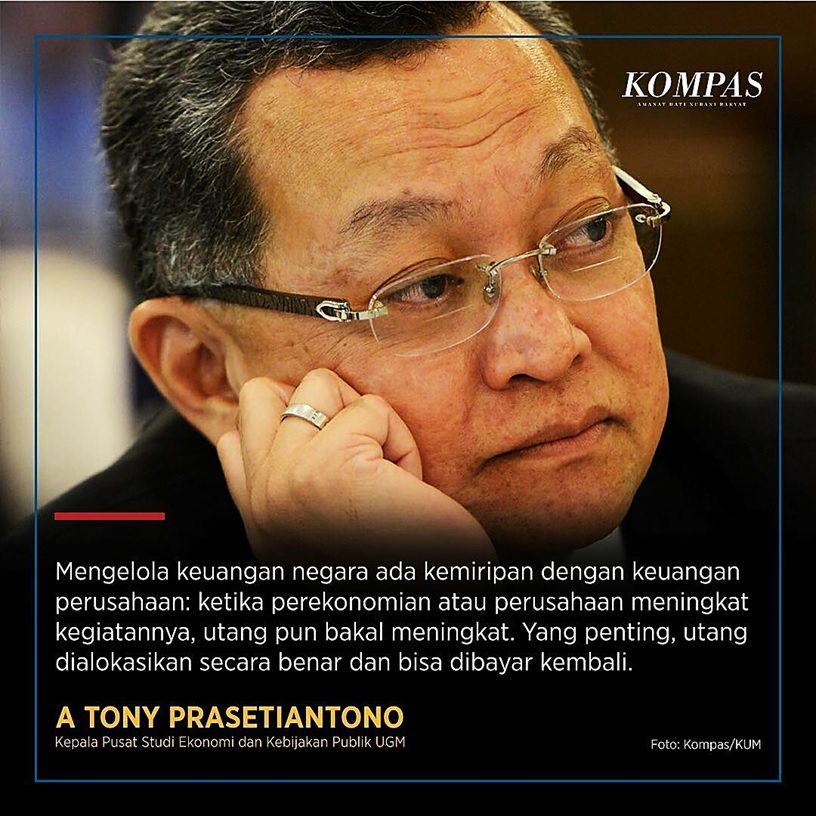



 Media Indonesia – Kolom Pakar, Senin 5 Maret 2018
Media Indonesia – Kolom Pakar, Senin 5 Maret 2018


