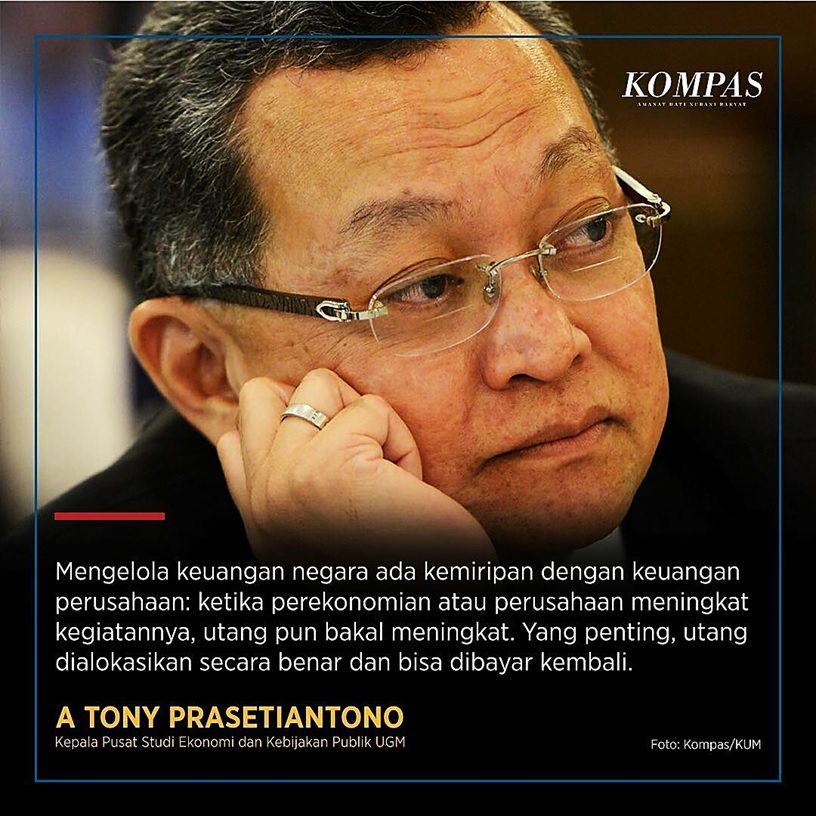
Kompas – Analisis Ekonomi, Selasa 20 Maret 2018
Bank Indonesia (BI) baru saja mengumumkan posisi terakhir utang luar negeri Indonesia, baik yang dilakukan oleh pemerintah dan BI maupun oleh swasta. Akhir-akhir ini banyak kritik terhadap penambahan utang oleh Indonesia. Dari satu sisi, kritik tersebut benar karena kita pernah mempunyai trauma berat tatkala mengalami krisis besar pada 20 tahun silam (1998) yang penyebab utamanya utang luar negeri. Namun di sisi lain, sebagian kritik tersebut tidak akurat, karena masalah utang memang mengandung banyak segi serta aneka data dan rasio-rasio, yang seringkali bisa disalahartikan (misleading).
Bahwa utang luar negeri Indonesia terus meningkat, hal itu memang tak terhindari. Mengelola keuangan negara ada miripnya dengan keuangan perusahaan: ketika perekonomian atau perusahaan meningkat kegiatannya, maka utangnya pun bakal meningkat. Yang penting, utang tersebut dialokasikan secara benar dan bisa dibayar kembali. Kata ekonom Alexander Hamilton (1781), salah satu pendiri AS, “Utang pemerintah, jika jumlahnya tidak berlebihan, sesungguhnya adalah sebuah rakhmat”. Maksudnya, utang memang diperlukan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan fiskal, asalkan masih terkendali.
Utang luar negeri Indonesia pada akhir Januari 2018 tercatat USD 357,5 miliar, yang terdiri dari utang pemerintah dan BI sebesar USD 183,4 miliar, serta utang swasta USD 174,2 miliar. Utang ini tentu saja meningkat dari waktu ke waktu. Dibandingkan saat krisis 1998 utang luar negeri kita “hanya” USD 130 miliar, yang dibagi rata antara utang pemerintah dan swasta. Namun pada saat itu cadangan devisa juga hanya USD 20 miliar. Berarti jumlah utang luar negeri setara dengan 6,5 kali lipat cadangan devisa.
Sedangkan posisi cadangan devisa kita saat ini USD 131 miliar. Berarti, volume utang luar negeri kita saat ini 2,7 kali lipat dibandingkan cadangan devisa. Artinya, intensitas utang luar negeri kita, meski secara nominal terus meningkat, namun secara riil menjadi lebih ringan. Cadangan devisa bisa diinterpretasikan sebagai proxy bagi kemampuan untuk membayar kembali.
Di masa lalu, berat-ringannya utang luar negeri biasanya dibandingkan dengan data ekspor. Namun dalam perkembangannya, data tersebut tidaklah bisa menggambarkan kemampuan membayar secara lebih obyektif. Karena di luar ekspor, sesungguhnya masih ada lagi ekspor dan impor jasa atau transaksi berjalan (current account). Selain itu, masih ada lalu lintas modal (capital account), yang jika dikombinasikan dengan transaksi berjalan dinamakan neraca pembayaran (balance of payments). Semua transaksi dalam lalu lintas devisa tersebut akan bermuara pada cadangan devisa, yang dalam 20 tahun terakhir berlipat 6,5 kali, sedangkan utang luar negeri berlipat 2,9 kali dalam periode yang sama. Berarti kondisi 2018 jauh lebih baik daripada 1998.
Kini, cara yang paling lazim digunakan oleh para ekonom adalah membandingkan utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Karena variabel ini dianggap menggambarkan secara obyektif kekuatan ekonomi suatu negara. Dalam situasi global seperti saat ini, “kewarganegaraan” modal menjadi tidak penting lagi. Yang terpenting, modal tersebut (dari mana pun asalnya) dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Dengan PDB Indonesia saat ini hampir USD 1 triliun (Rp 13.000 triliun), maka posisi utang luar negeri kita terhadap PDB adalah 35 persen. Ini masih di bawah batas toleransi 60 persen sebagaimana disyaratkan UU Keuangan Negara. Di kelompok negara yang sebanding (peer group), rasio terbaik dicapai oleh Afrika Selatan (12,4 persen), lalu India (26), Filipina (32). Indonesia selevel dengan Brasil dan Thailand (34), dan lebih baik daripada Meksiko (39), Turki (54) dan Malaysia 68).
Yang menarik, di negara-negara maju, rasio utang terhadap PDB-nya justru lebih jelek: AS dengan 106 persen dan puncaknya Jepang 250 persen. Namun, kita tidak bisa membandingkannya. Utang pemerintah Jepang memang besar, namun itu dilakukan terhadap rakyatnya sendiri. Obligasinya dijual di pasar domestik, dengan utang berdenominasi yen. Pemerintah AS juga utangnya banyak, namun dalam dollar AS.
Ini berbeda dengan utang pemerintah negara-negara berkembang, yang sebagian berupa valuta asing. Dalam kasus Indonesia, komposisinya adalah 36 persen berbentuk rupiah dan 64 persen valuta asing. Dengan kata lain, membandingkan utang luar negeri Indonesia dengan Jepang dan AS tidaklah apple to apple, karena beda komposisi.
Negara donor pemberi utang terbesar kepada Indonesia melalui skema bilateral adalah Jepang, yang sudah mulai intens masuk ke Indonesia sejak 1970. Negara donor lain yang berada jauh di bawah Jepang: Perancis, Jerman, Korea Selatan, China dan AS. Dalam beberapa tahun terakhir, China tumbuh paling cepat. Selain itu, masih ada utang luar negeri dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia, IMF, ADB dan IDB.
Meski utang luar negeri Indonesia masih dalam kategori aman, tentu saja tidak berarti kita tidak berbuat sesuatu untuk menekan dosisnya. Insiatif pemerintah melalui kebijakan amnesti pajak, sesungguhnya merupakan salah satu cara untuk memperbesar basis penerimaan pajak, agar ketergantungan pada pembiayaan defisit fiskal bisa digeser dari utang menjadi penerimaan pajak. Amnesti pajak bertujuan untuk “mengail” potensi penerimaan pajak yang sebelumnya “tersembunyi”.
Namun ternyata hasilnya belum sesuai ekspektasi, meskipun masuknya dana repatriasi USD 12 miliar dari luar negeri layak diapresiasi. Angka ini signifikan dalam menaikkan cadangan devisa kita. Ke depan, pemerintah harus tetap konservatif dalam berutang, dengan menjaga defisit APBN di bawah 3 persen terhadap PDB. Tahun ini, target defisit adalah 2,19 persen.
Selain itu, Kementerian Keuangan terus berupaya menyisir potensi pajak yang belum terungkap. Namun terkadang agresivitas upaya tersebut harus terkendala oleh perekonomian yang lesu. Dilema antara menarik utang luar negeri atau menarik pajak domestik inilah yang selama ini tidak mudah dikompromikan.
*A. Tony Prasetiantono, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM;Faculty Member Bank Indonesia Institute.
